
Oleh Moh. Mudzakkir, Ph.D. | Pemimpin Redaksi Warta PTM – Wakil Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Dalam kehidupan kontemporer, manusia tidak lagi hanya berada di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Kita hidup di dua dunia sekaligus, dunia fisik dan dunia digital yang saling berkelindan membentuk pola baru dalam bekerja, belajar, berinteraksi, bahkan membangun identitas diri. Di ruang digital, kita menemukan peluang besar: belajar dari universitas dunia tanpa harus meninggalkan rumah, membuka usaha daring dengan jangkauan global, dan berpartisipasi dalam wacana publik secara terbuka. Namun, di balik segala peluang itu, tersembunyi kesenjangan yang halus tetapi nyata. Tidak semua orang memiliki kemampuan, sumber daya, atau kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan dunia digital.
Teknologi yang Tidak Pernah Netral
Sering kali kita berpikir bahwa teknologi bersifat netral, hanya alat yang bisa digunakan untuk tujuan baik atau buruk, tergantung pada siapa yang memegangnya. Namun, sosiologi masyarakat dan teknologi justru mengajarkan sebaliknya. Teknologi selalu lahir dari konteks sosial tertentu; ia memuat nilai, ideologi, bahkan kepentingan ekonomi dan politik yang melekat di dalam desainnya (Bijker & Pinch, 1987).
Ambil contoh algoritma media sosial. Ia bukan sekadar mesin yang mengatur apa yang kita lihat di layar. Ia adalah sistem yang memprioritaskan konten berdasarkan “perhatian,” bukan “manfaat.” Akibatnya, mereka yang memiliki kemampuan teknis dan sumber daya besar, misalnya influencer dengan modal finansial dan jaringan luas, lebih mudah “terlihat” dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Sementara itu, kelompok dengan literasi digital rendah atau perangkat terbatas menjadi sekadar konsumen pasif, yang waktu dan datanya dikonversi menjadi keuntungan bagi pihak lain.
Fenomena ini mengingatkan kita pada konsep time–space distanciation yang dikemukakan Anthony Giddens (1990): teknologi memperluas jangkauan ruang dan waktu manusia, tetapi juga menciptakan jarak baru bagi mereka yang tidak punya akses. Dunia menjadi terhubung, namun tidak semua dapat ikut terlibat.
Di Indonesia, ketimpangan digital tampak nyata. Menurut survei APJII (2024), penetrasi internet nasional mencapai 79,5 % atau sekitar 221 juta pengguna, tetapi kontribusi wilayah non-urban hanya 30,5 %. Artinya, penggunaan internet masih terpusat di kota besar dan kalangan menengah ke atas. Penelitian Bank Dunia (2023) juga menunjukkan bahwa keluarga dengan pendapatan dan pendidikan rendah memiliki kemungkinan jauh lebih kecil untuk mengakses internet atau memiliki perangkat digital yang memadai. Keadaan ini menandakan adanya jurang struktural dalam kesempatan digital.
Modal Sosial di Era Digital: Membaca dengan Kacamata Bourdieu
Pierre Bourdieu (1986) memberi kita kacamata tajam untuk membaca situasi ini. Menurutnya, dalam praktik kehidupan masyarakat tersusun oleh berbagai bentuk modal: ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Semua modal itu menentukan posisi seseorang dalam arena sosial, termasuk arena digital.
Dalam dunia digital, modal ekonomi menentukan kemampuan seseorang untuk memiliki gawai canggih, koneksi internet cepat, dan perangkat lunak berbayar. Modal budaya berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengolah informasi digital secara kritis—yang sering kali diperoleh dari pendidikan dan lingkungan keluarga. Modal sosial tampak dalam jaringan relasi digital—berapa banyak koneksi profesional di LinkedIn, komunitas daring yang diikuti, atau dukungan sosial yang diperoleh di ruang digital. Sementara modal simbolik hadir dalam bentuk status, reputasi, dan pengakuan digital: siapa yang “diverifikasi,” siapa yang berpengaruh.
Coba lihat di sekitar kita. Seorang mahasiswa kota dengan laptop dan koneksi stabil bisa membuat konten edukatif di YouTube atau bergabung dalam internasional online class. Namun di desa lain, masih ada siswa yang harus memanjat bukit mencari sinyal demi mengirim tugas sekolah. Kedua-duanya hidup di era digital, tapi peluang mereka berbeda. Dalam istilah Bourdieu, yang pertama memiliki modal digital berlapis, sementara yang kedua kekurangan modal dasar untuk bersaing.
Penelitian di Indonesia (East-South Institute, 2023) menemukan bahwa kesenjangan akses teknologi dan keterampilan digital tidak hanya berdampak pada kemampuan ekonomi, tetapi juga pada integrasi sosial dan kepuasan hidup. Mereka yang tertinggal secara digital cenderung merasa terpinggirkan dalam pergaulan sosial maupun kesempatan kerja. Dengan kata lain, kekurangan modal digital berarti kehilangan ruang partisipasi dalam masyarakat modern.
Reproduksi Sosial di Dunia yang Terkoneksi
Ketimpangan ini bukan sekadar soal perangkat, melainkan juga soal reproduksi sosial. Bowles dan Gintis (1976) menjelaskan bahwa sistem pendidikan dan struktur sosial kerap mempertahankan ketimpangan kelas melalui mekanisme halus yang tampak “alami.” Di era digital, proses ini menemukan bentuk baru. Algoritma media sosial, sistem perekrutan daring, hingga ekonomi platform seperti ojek online atau freelancer digital memperkuat logika lama: yang punya modal lebih besar akan lebih mudah naik kelas.
Bayangkan dua anak muda: satu dari keluarga menengah kota yang terbiasa dengan komputer sejak kecil, satu lagi dari keluarga buruh yang baru mengenal ponsel pintar di bangku SMA. Keduanya hidup di dunia yang sama, tapi ketika satu mampu membuka bisnis daring dan membangun personal branding, yang lain berjuang bertahan dalam pekerjaan digital berisiko tanpa jaminan sosial. Dunia digital, yang seharusnya menjanjikan mobilitas sosial baru, justru berpotensi memperkuat stratifikasi lama dalam wujud yang lebih halus dan algoritmis.
Kajian sub-nasional di Indonesia menunjukkan bahwa wilayah dengan kapasitas ekonomi dan infrastruktur digital rendah, khususnya luar Jawa, tertinggal jauh dalam pengembangan teknologi rumah tangga maupun keterampilan digital individu (Kurniawati, Yap & Zhang, 2023). Hasil serupa juga ditemukan oleh Rajagukguk et al. (2024) yang menjelaskan bahwa lokasi geografis dan tingkat ekonomi rumah tangga sangat memengaruhi tingkat penggunaan internet dan literasi digital di Indonesia. Ketimpangan digital ini membuat reproduksi sosial tidak hanya terjadi di sekolah atau dunia kerja, tetapi juga di setiap klik dan koneksi internet.
Akses Digital sebagai Agenda Publik dan Kebijakan
Karena itu, akses digital tidak bisa hanya dianggap sebagai urusan teknis atau komersial. Ia adalah persoalan keadilan sosial. Dalam masyarakat informasi, hak atas internet dan literasi digital sama pentingnya dengan hak atas pendidikan. Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil harus melihat isu ini sebagai bagian dari agenda publik.
Kebijakan digital inclusion harus melampaui pembangunan infrastruktur jaringan. Ia perlu menyentuh aspek literasi digital kritis, kemampuan memilah informasi, memahami etika berkomunikasi, hingga kesadaran tentang jejak digital dan keamanan data pribadi. Laporan UNICEF (2023) menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, masih menitikberatkan pada penyediaan akses fisik ketimbang pemerataan kemampuan dan partisipasi digital yang bermakna. OECD (2023) menambahkan bahwa keadilan digital sejati harus berfokus pada “equitable outcomes,” bukan sekadar “equal access.”
Di Indonesia, data Kementerian Kominfo (2023) memperlihatkan Indeks Literasi Digital Nasional masih berada di angka 3,54 (skala 1–5). Ini menunjukkan bahwa kemampuan kritis dan kesadaran etis masyarakat digital belum sepenuhnya matang. Sementara itu, UNDP (2024) menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan indeks inklusivitas digital yang kuat agar digitalisasi tidak justru memperlebar jurang sosial.
Teknologi sebagai Sarana Emansipasi
Kita hidup di masa ketika teknologi tampak semakin “cerdas,” tetapi seringkali justru membuat manusia kehilangan arah. Padahal, teknologi seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan penentu nasib. Dunia digital bisa menjadi ruang produksi sosial—tempat ide, inovasi, dan solidaritas lahir—jika kita menggunakannya untuk memperkuat kolaborasi dan kesetaraan.
Pertanyaan mendasarnya bukan lagi “Seberapa cepat kita menyesuaikan diri dengan teknologi?”, melainkan “Seberapa adil teknologi bekerja bagi semua lapisan masyarakat?” Sebab kemajuan digital sejati tidak diukur dari seberapa canggih perangkat yang kita miliki, tetapi dari seberapa luas peluang yang kita buka bagi semua orang untuk tumbuh bersama.
Masa depan digital Indonesia akan benar-benar cerah jika ia menjadi ruang inklusif—di mana setiap orang, apa pun latar belakang sosialnya, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi. Dunia digital seharusnya menjadi jembatan kesetaraan, bukan tembok baru yang memisahkan yang punya dan yang tak punya. Itu harapannya, demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Semoga.
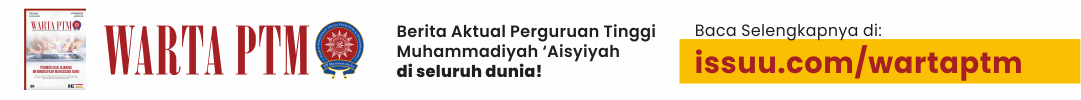
Be the first to comment